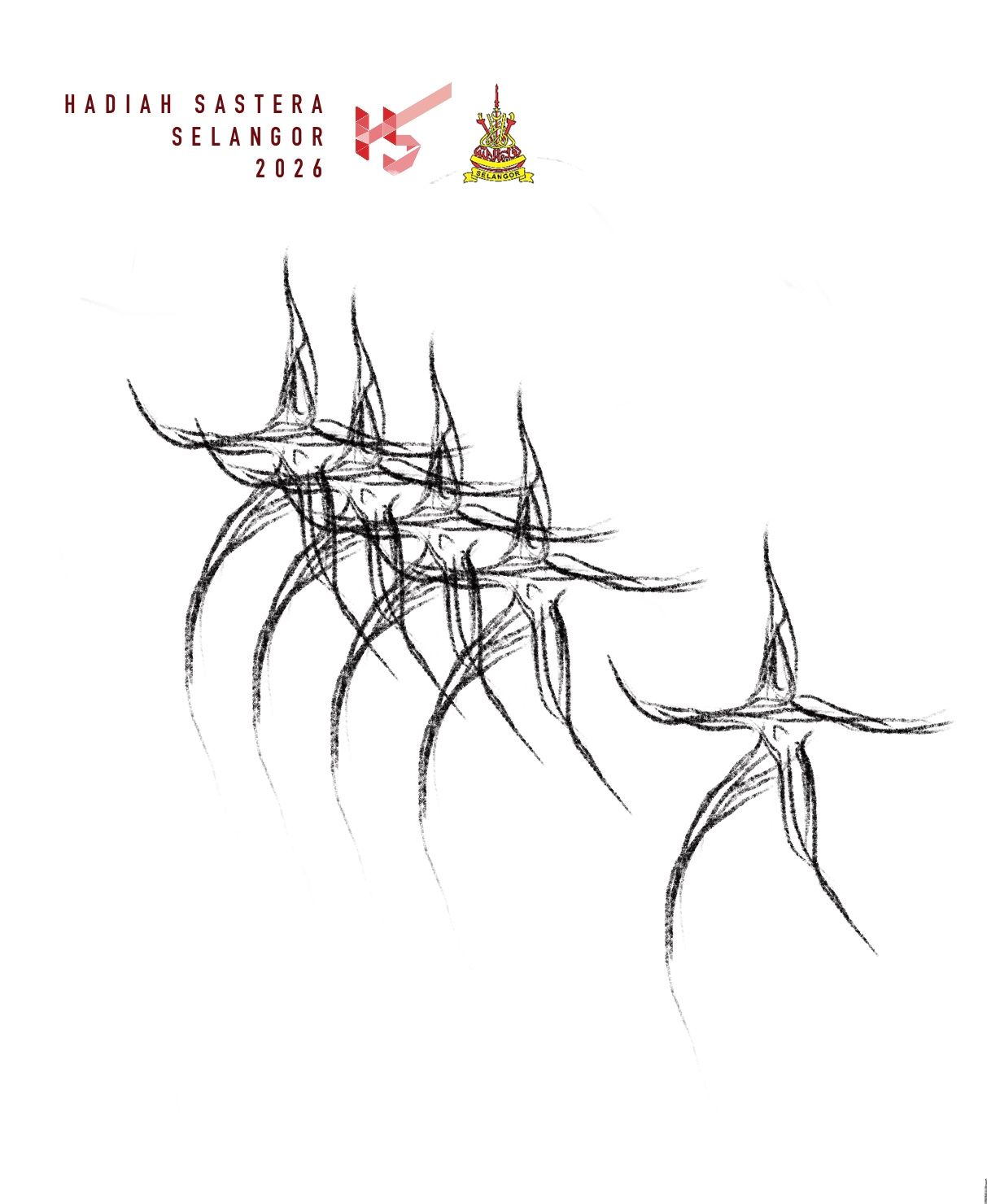Oleh Zulzafry Zulkifly
Ketika mahu memulakan cerita ini, aku perasan * tertanggal daripada papan kekunci entah ke mana. Aku cuba mencarinya di bawah meja, di bawah kerusi, di celah-celah selirat wayar, di bawah skrin monitor, di belakang PC, di bawah keyboard dan di sekeliling kamar. Tapi kelibatnya tak berjaya dijumpai.
Ke manakah pergi huruf itu? Entah mengapa dia tiba-tiba mogok dan terus menghilangkan diri. Aku perhati setiap abjad, angka dan simbol yang masih setia pada 61 kekunci papan. Beberapa aksara sudah mula cacat sifatnya dek selalu diketik. Tapi dalam minda, aku masih ingat huruf dan letaknya. A di hujung kanan dan B di sebelah N.
Kehilangan * mencacatkan pandangan. Satu lompong yang membantutkan ilham. Tak boleh jadi. Bagaimana mahu memulakan cerita tanpa keberadaannya?
Aku cuba mempersetankan kehilangannya dan mula mengarang. Tangan kiri terasa pegal. Kekok. Hujung jari telunjuk dan ibu jari menyuarakan kejanggalan. Lompong itu mengalir dari papan kekunci di hujung jari terus ke minda menyebabkan gagal membuahkan apa-apa suku kata dan perkataan. Ilham turut sama hilang dengan *.
Sejak bila * menjadi begitu penting untuk cerita? Selama menulis, tidak pernah sekalipun aku menggunakannya. Malah, mata akan terasa aneh melihat keberadaannya pada skrin. Seakan-akan membuka laman tidak halal.
Apatah lagi lidah Melayuku yang tidak pernah kenal sebutannya. Fonetiknya, bagaimana? Eks? Za? Ksa? Sa? Bahasa ini memang tak pernah melayaninya dengan baik. Sewajarnya, huruf itu terus disingkirkan dari daftar abjad.
Jadi aku putuskan untuk keluar rumah. Mencari * dan ilham yang entah bergantungan di mana-mana. Mungkin rasa pegal di jariku akan hilang jika keluar. Udara segar, sinar mentari siang hari dan desir angin pada daun pohon selalu menjemput ilham datang bertamu.
Jika diizinkan Tuhan, dalam langkahku mungkin akan terjumpa kelak huruf * yang tergeletak di tepi jalan. Akan kukutip dan bawa pulang. Selepas itu, ceritaku akan selesai. Ilham akan kembali lancar.
Tapi ke mana pun aku pergi, aku diingatkan kepada * yang hilang. Ia ada di mana-mana. Di tepi jalan, di tiang elektrik, di warung, di hadapan rumah ibadat, di rumah-rumah pentaksub dan gerbang selamat datang kampung.
Semua orang dan benda ingin mengejekku kerana kehilangan *. Pak Mat yang berniaga di warung tepi jalan itu tersengih-sengih melihatku dari kaunternya. Aku tahu dia tidak tahu bagaimana menyebut huruf itu. Huruf V saja bertukar menjadi B di lidahnya, apatah lagi *. Tapi dia berlagak mahu orang tahu, dialah empunya * terbesar. Di anjung warung, bergantung dari atap hingga hampir-hampir mencium tanah, sebesar-besar kain rentang dengan * paling gadang. Memang dia mahu orang tahu yang *nyalah yang paling besar.
Aku abaikan Pak Mat dan sengihnya lalu terus melangkah. Sambil-sambil, aku mengutip sebutir dua * yang terbaring di tanah. Menilik dan berkira-kira sama ada ia boleh menggantikan *ku.
Namun walau macam mana pun aku cuba, * yang bergelimpangan itu tidak akan mampu menggantikan *ku yang hilang. Sama ada ia terlalu besar atau terlalu kecil untuk petak lompong di papan kekunci.
*-* itu mengingatkan aku kepada seorang teman bernama Ilham. Kalau ada manusia yang tidak ambil tahu tentang *, Ilhamlah orangnya. Dia tidak tahu nilai sebutir * walau berbuih mulutku mengajar angka roman.
Angka roman menggunakannya sebagai 10. Dua * bermaksud dua puluh. Angka selepasnya, sama ada I, II, III atau IV menunjukkan nilai sa. Dua puluh satu adalah **I, dua puluh dua adalah **II dan seterusnya.
Berkali-kali kuulang tapi otaknya memang tidak dapat menerima walau sedikit.
Bagi Ilham, * bernilai RM50, bukan 10 seperti yang didakwa orang Romawi. Kerana itu setiap beralih penggal, dia akan menjual *nya kepada orang-orang yang sanggup membeli. Paling kurang pun, dia akan beroleh wang buat mengisi top up.
Mungkin ada baiknya jika aku menelefon Ilham, bertanya jika dia masih punya baki *. Kalau dia minta 50 ringgit pun, akan kubayar tunai.
“Hello,” suara Ilham atas talian dari belah sana.
“Aduh, aku dah jual semua * aku. Kau tahulah, sekarang kan musimnya. Kalau aku tidak jual sekarang, lepas ini tak laku dah. Masa-masa ni lah kena pandai buat duit. Paling kurang, dapat bantuan makanan,” jawab Ilham setelah aku tanyakan soalan dan suarakan permintaan.
“Kau dah jual kau punya ke sampai kena minta aku?” tanya Ilham lagi.
Aku beritahu yang aku punya * telah hilang daripada papan kekunci. Sekarang mahu menulis sedikit tapi tak boleh sebab * aku hilang.
“Kau bukan pernah guna pun sebelum ini selama aku baca semua tulisan kau. Kenapa sekarang terhegeh-hegeh mahu cari? Kau mahu bertanding?”
“Kau mana tahu dilema penulis musim-musim ini,” jawabku lalu tamatkan panggilan.
Keputusan untuk keluar rumah ternyata sia-sia. Ilham tak dapat menolongku dan semua * di tepi jalan ini tiada guna. Kalau kukumpul semua * sekalipun, tiada perubahan akan berlaku.
Berang dengan Ilham, aku terus menapak. Tapi setiap langkah, terus mengingatkan aku kepada *. Kepada kecuaianku, kepada ketidakpedulianku, kepada negaraku.
Kehilangan * menjadikan aku sasau. Lebih edan daripada wajah-wajah yang bergantung di samping setiap * di pinggir jalan.
Hingga akhirnya, aku buat keputusan untuk pulang. Cerita akan kutulis meski tanpa *. Biarlah tanganku pegal dan gatal, akan kugesa juga jari jemari terus menari di papan kekunci. Lagipun selama negara merdeka, * tidak pernah memberi apa-apa makna kecuali menyempurnakan 26 daftar huruf.
Malah, tanpa menggunakan huruf * pun ceritaku akan tetap difahami. Orang kita sudah pandai membezakan mana satu emas, tembaga dan tin kosong.
Maka aku pulang, mula mengarang sebuah cerita yang sedari awal melompat-lompat di benak. Sebuah cerita dengan jumlah * paling banyak dalam sejarah tapi tidak sebutir pun ditulis. Aku buat keputusan untuk gantikan * dengan * dan berharap pembaca seorang yang pandai.