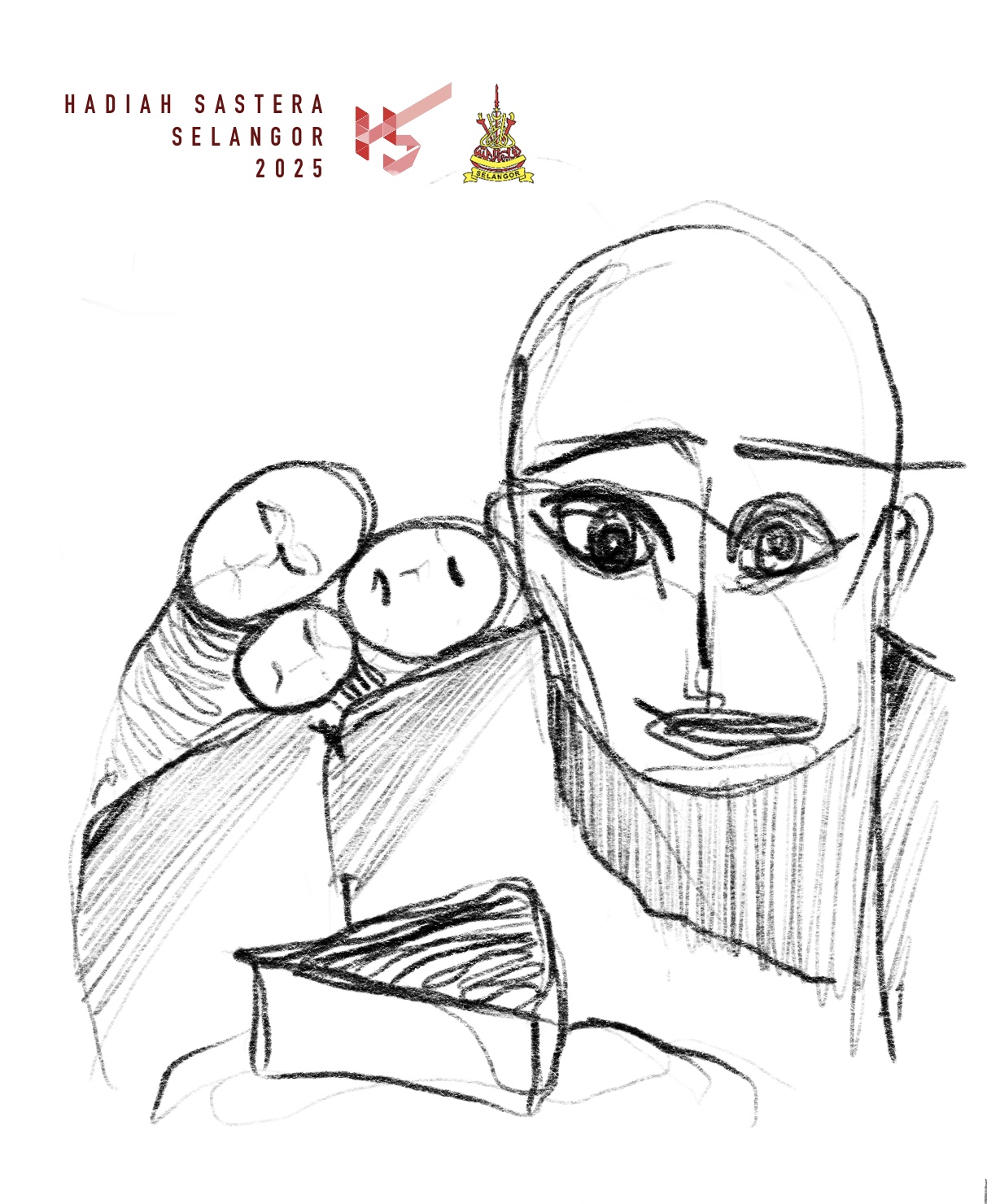Oleh Lokman Hakim
Sepotong kek badam hancur lumat di atas lantai. Ibu, ayah dan adik saya bergelimpangan. Sejalur cahaya rembulan tembus menerangi dari kaca tingkap yang pecah. Saya merenung bagaimana cahaya bulan itu menyinari cebisan kek badam. Itulah satu-satunya makanan kami pada bulan ini. Dan kini ia sudah tiada. Tidak, ia masih ada, tapi keluarga saya sudah tiada untuk menjamahnya.
Insiden ini sebermulanya dengan pertengkaran kecil. Khamis, si adik, mendakwa saya telah menyajikan kek badam haram sesudah sepotong kek badam yang diperuntuk untuk kami bulan ini habis dimakan tak sampai sepuluh hari. Saya memberitahunya saya tiada pilihan. Jiran sudah mati kelaparan ketika potongan kek badam mereka tiba di depan pintu. Saya cuma enggan membazirkan makanan yang tidak akan dimakan itu. Semua orang tahu, sepotong kek badam tidak mampu mengenyangkan perut seorang individu apatah lagi sebuah keluarga selama sebulan.
“Carilah keberkatan dalam mencari rezeki, Razali! Ada seribu satu cara halal selain merampas kek badam jiran!”
Ibu membisu. Ayah pikun. Khamis terlalu idealis, fikir saya. Mencari kerja sambilan dalam sistem sedia ada itu adalah enigma. Saya harus punya pendidikan tahap tertinggi. Harus punya pengalaman kerja selama 10 tahun. Namun kerja yang saya miliki sekarang hanya membayar saya dengan sepotong kek badam. Rumah dan segala keperluan lainnya ditanggung syarikat. Kononnya. Saya bekerja syif pagi dan syif malam. Berehat sebentar cuma, sejam dua untuk makan sebelum menyambung syif seterusnya. Saya hanya ada sebuah pekerjaan yang menuntut kehidupan saya tuntas dengan nilai sepotong kek badam.
Mendengar kata-kata Khamis yang baru sahaja menghamburkan potong kek badam yang saya kutip dari depan rumah jiran tadinya membuat saya tidak berdaya. Saya baru sahaja berpeluang untuk bercuti hari ini dengan harapan untuk menghilangkan lelah. Tidur seharian sudah memadai. Malangnya, peluang itu tidak ada hari ini.
“Jika kau tak habiskan kek badam tu, aku takkan buat macam ni, Khamis!” bentak saya sebelum baring membelakangkan mereka sambil menghadap dinding.
Di televisyen, iklan perihal makanan kesihatan yang kini jadi makanan utama kami - sepotong kek badam terus-menerus disiarkan. Secubit dikatakan dapat membekalkan tenaga sepanjang hari. Saya mahu percaya perkara itu tetapi bekerja di bawah terik matahari dan dingin malam yang menggigit hingga ke tulang menzahirkan betapa secubit kek badam itu tidak memadai. Saya harus keluar dari kerangka kerja yang begitu menzalimi waktu saya itu supaya saya beroleh pendapatan tambahan. Sepotong kek badam untuk sebulan tidak memadai. Itu hakikat.
Ibu mengutip serpihan kek badam di atas lantai. Lalu diletakkan ke dalam bekas. Diletak pula bekasnya di atas meja. Ayah mengambil tempat di tengah-tengah ruang tamu lalu duduk bersila.
“Kita berada dalam darurat, Khamis! Darurat! Kamu tahu Razali tidak dapat cari kerja lain. Dan kamu patut tahu tiada kerja yang bersesuaian di luar sana!”
Mendengar kata-kata ayah, Khamis berteleku lalu menangis. Dia memang tidak berupaya untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana, lebih-lebih lagi dengan keadaan fizikalnya yang tidak begitu sempurna akibat kemalangan jalan raya beberapa tahun lepas. Saya fikir, saya tidak boleh sekadar berpeluk tubuh begini. Saya harus lebih berikhtiar. Saya bingkas lalu melangkah keluar dari rumah.
Bukanlah tiada kerja lain, hanya saya tidak berusaha lebih. Usia menginjak 40 tahun, saya dikatakan terlebih layak. Pekerjaan di sebuah syarikat yang kekurangan pekerja sentiasa akibat ketidakmampuannya menjaga kebajikan pekerja memerangkap saya dengan tawarannya. Saya harus keluar dari sana. Saya harus bina rangkaian sahabat yang pandai berniaga. Peluang pasti lebih cerah jika saya ada keberuntungan sebegitu. Saya harus bawa keluarga saya keluar dari kemelut ini. Kepala serasa akan meletup. Saya harus menjernihkan fikiran dengan berjalan-jalan di kota. Mencari ilham menuntut diri untuk keluar dari rutin. Akal itu ada tetapi kenapa serasa pilihan yang seribu satu jumlahnya terlihat ilusi pula?
Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan kaki. Telefon bimbit pula tidak dibawa. Saya pasti keluarga saya risau. Lalu saya berpatah balik. Saya tenung langit dengan bulan yang dikaburi awan. Saya harap malam tidak berakhir selama-lamanya. Saya enggan mendepani esok kerana saya harus kembali ke tempat kerja yang begitu memenatkan itu.
Di luar rumah, saya lihat ambulans dan juga polis sudah berkumpul. Saya sedar pasti ada sesuatu yang tidak baik sudah berlaku. Saya bergegas ke dalam rumah tanpa menghiraukan polis yang menghalang.
“Khamis! Ayah! Ibu!”
“Sabar, encik! Sabar!” tegas pegawai polis yang bertugas. Saya baru teringat bahawa terdapat sistem perlindungan digazetkan ke atas setiap potongan kek badam yang disediakan untuk setiap rumah. Ia tidak boleh diambil oleh orang lain selain pemilik rumah. Racun akan disuntik ke dalam makanan melalui bekas yang melitupi potongan kek badam itu. Bagaimana saya boleh lupa semua itu? Apakah ini hukuman dari Tuhan di atas ketidakmampuan saya keluar daripada belenggu masalah ekonomi yang mencengkam keluarga kami?
Sepotong kek badam hancur lumat di atas lantai. Ibu, ayah dan adik saya bergelimpangan. Sejalur cahaya rembulan tembus menerangi dari kaca tingkap yang pecah. Saya merenung bagaimana cahaya bulan itu menyinari cebisan kek badam. Itulah satu-satunya makanan kami pada bulan ini. Dan kini ia sudah tiada. Tidak, ia masih ada, tapi keluarga saya sudah tiada untuk menjamahnya.